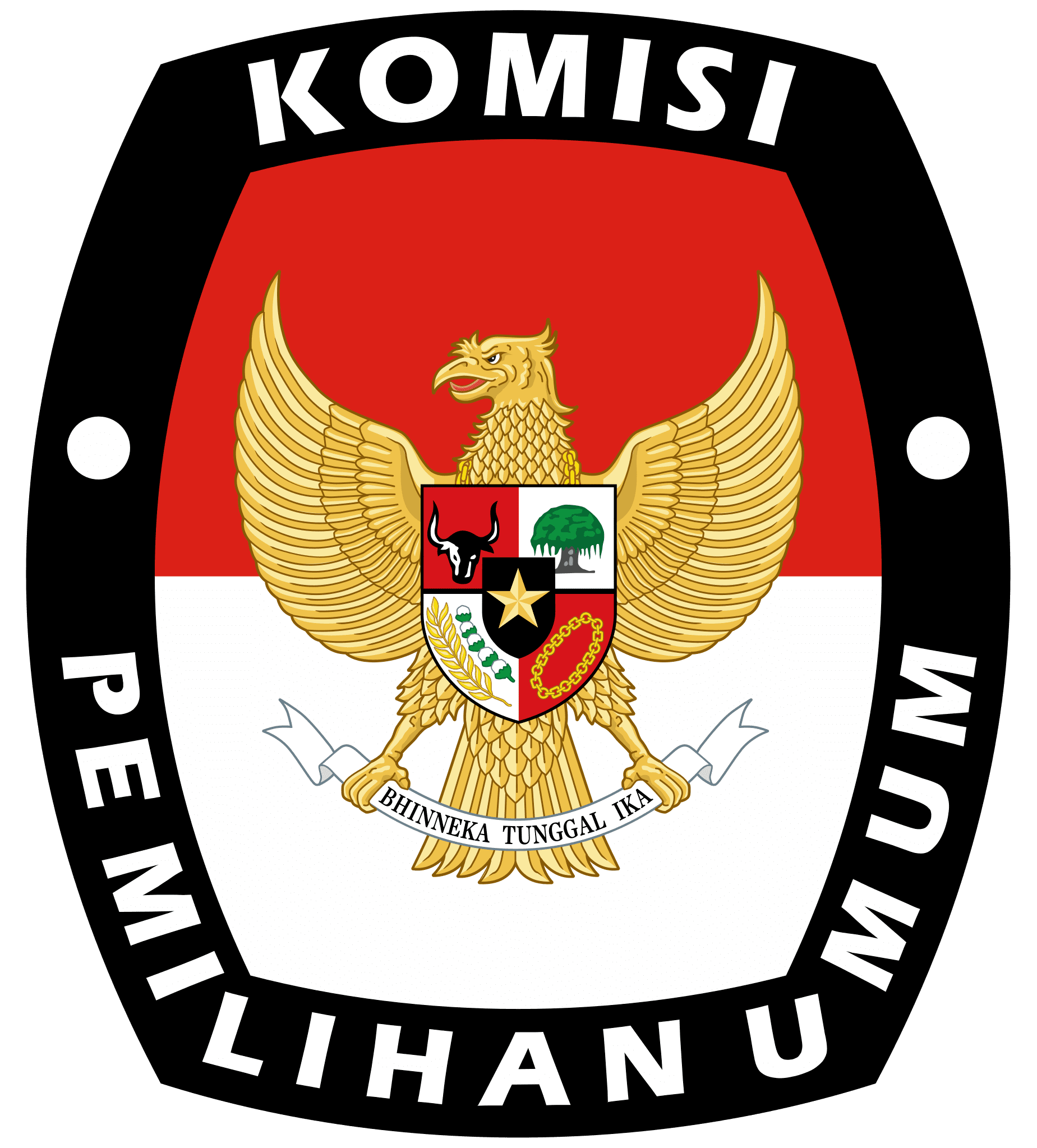KEKUATAN POLITIK : REKRUTMEN DAN KEPEMIMPINAN
(Oleh: Ali Syaifa AS, S.IP) Kehadiran pemimpin selalu dibutuhkan oleh setiap kelompok masyarakat. Baik pada masyarakat yang paling primitif, maupun pada masyarakat yang paling modern sekalipun. Hal ini dikarenakan, di dalam kehidupan bersosial dan bermasyarakat muncul seribu macam persoalan untuk diselesaikan dan ada seribu macam keinginan untuk dapat diwujudkan. Oleh karena itu hadirnya pemimpin ditengah masyarakat menjadi penting dan dibutuhkan dalam rangkat mengatur, memimpin, dan mengkonsolidasikan segenap sumber daya (resources) yang ada ditengah masyarakat untuk mengurai dan memecahkan berbagai macam masalah serta dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dan harapan masyarakat. Beragam persoalan yang muncul merupakan akibat dari interaksi manusia dengan sesama manusia maupun manusia berinteraksi dengan alam. Ada kecenderungan manusia pada dasarnya berwatak egois dan ingin menang sendiri. Latar belakang inilah terkadang yang membuat hubungan manusia (human relations) dengan manusia lainnya tidak berjalan secara baik dan setara. Terkadang yang kuat sewenang-wenang kepada yang lemah. Terkadang yang kaya menindas kepada yang miskin. Pada kasus ini kehadiran pemimpin menemukan relevansinya untuk mengambil peran mengatur kehidupan bermasyarakat agar tercipta kesetaraan, keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan bersama. Begitu juga dalam relasi manusia dengan alam, seringkali manusia tidak memanfaatkan alam secara arif dan bijaksanan. Seringkali dikarenakan ambisi keduniawian manusia yang tinggi dan tidak mudah puas. Manusia mengeksploitasi alam dan mengakibatkan kerusakan parah pada alam dimana-mana. Pepohonan ditebang sesukanya sampai mengakibatkan hutan gundul. Sampai pada waktunya hujan lebat tiba terjadilah bencana longsor dan banjir dimana-mana. Itu secuil contoh yang menggambarkan malapetaka yang terjadi diakibatkan keserakahan dan kerakusan manusia didalam memanfaatkan alam ini. Oleh karena itu, seorang pemimpin menenemukan relevansinya kembali didalam mengatur masyarakat agar berinteraksi dengan alam secara arif dan bijaksanan sehingga tercipta keseimbangan dan keharmonisan. Dalam masyarakat yang semakin modern. Jika mengacu kepada pernyataan dari Samuel P. Huntington (1996) bahwa akhir dari persekutuan manusia adalah terbentuknya negara-bangsa (nation-state). Maka, dapat kita simpulkan bahwa masyarakat modern adalah masyarakat yang ada pada sebuah negara. Seperti halnya negara Indonesia ini, sosok pemimpin masyarakat tertinggi adalah pemimpin politik atau Pemerintahan. Karena politik adalah panglima dari aspek kehidupan manusia lainnya. Begitu menurut pandangan ilmuwan politik pertama Indonesia, Prof. Miriam Budiarjo (Budiarjo, 2007: 13). Solidaritas Masyarakat Keberhasilan seorang pemimpin politik diukur dari bagaimana ia dapat menciptakan persatuan di masyarakat. Sehingga masyarakat dapat merasakan kondisi keadilan, perasaan senasib dan sepenanggungan. Ibnu Khaldun (1332 M-1406 M), seorang filolosof muslim yang terkenal menggunakan istilah solidaritas (ashobiyah). Bahkan menurutnya sebuah komunitas masyarakat atau negara akan tetap ada dan tidak akan hancur tercerai berai apabila ada perasaan solidaritas pada setiap komponen masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa solidaritas adalah merupakan kekuatan politik. Kualitas pemimpin sangat dipengaruhi oleh cara ia memimpin masyarakatnya. Cara memimpin itu secara sederhana diartikan sebagai kepemimpinan. Kecakapan seorang pemimpin itulah kepemimpinan. Mengenai istilah kepemimpinan pada dasarnya berhubungan dengan ketrampilan, tingkat kecakapan, dan tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang (Syam, 2009: 187). Di dalam catatan sejarah bangsa ini, pernah terjadi protes yang dilakukan oleh masyarakat terhadap para penguasa politik atau pemerintah. Sekedar mengingatkan aksi demontrasi besar-besaran pada tahun 1998 adalah bentuk kekecewaan masyarakat Indonesia terhadap penguasa atau pemerintahnya dan berujung pada lengsernya penguasa dan menuntut pergantian sistem politik yang lebih bersih dan lebih baik. Hal itu menunjukan bahwa keruntuhan politik selalu diawali oleh hilangnya solidaritas masyarakat karena kehilangan kepercayaan pada pemimpinnya karena gagal dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dan harapan masayarakat. Oleh karenanya, solidaritas atau perasaan senasib dan sepenanggungan dimasyarakat tidak bisa dianggap enteng oleh seorang pemimpin politik. Karena ia sangat menentukan keberlangsungan dan eksistensi suatu negara. Bersama masyarakat pemimpin akan menjadi kuat. Pemimpin politik harus sungguh-sungguh membangun solidaritas dimasyarakat. Ada 2 (dua) jalan agar solidaritas masyarakat dapat tercipta dan terwujud. Pertama, Proses recrutmen pemimpin politik harus berjalan melalui proses kompetisi yang terbuka dan adil. Kedua, Kepemimpinan politik yang berkarakter dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Kita bersyukur bahwa di Indonesia, proses pengisian jabatan politik dilakukan melalui mekanisme dan recrutmen yang jelas. Jabatan politik adalah mereka yang menduduki jabatan puncak pada lembaga eksekutif, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Jabatan politik di rumpun eksekutif pada level nasional adalah Presiden dan Wakil Presiden. Sementara pada level daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati atau Walikota beserta wakilnya. Mereka itu, sesuai regulasi yang mengaturnya dipilih melalui proses Pemilihan Umum (pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) yang dilaksanakn setiap 5 (lima) tahun sekali yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Ketentuan ini dapat ditemukan pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E. Jadi penting, sebuah kontestasi dan kompetisi di dalam Pemilu dan Pilkada dilaksanakan secara terbuka, fair, dan transparan. Hanya dengan cara itu, legitimasi politik dapat diwujudkan. Ingat, semakin tinggi tingkat legitimasi akan sangat mempengaruhi kulitas solidaritas di masyarakat. legitimasi yang rendah akan memicu perpecahan dan penolakan pada hasil pemilu dan pilkada serta lemahnya kepemimpinan politik. Proses kontestasi dan kompetisi didalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sepenuhnya diatur dan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai kewenangan yang dimilikinya yang diamanahkan oleh UUD 1945. Sejauh ini, mengacu kepada pelaksanan pemilu terakgir pada tahun 2019 dan Pilkada terahir pada 2020. Proses kontestasi dan kompetisi berjalan panas, sengit, dank keras. Namun, tetap sesuai dengan koridor aturan yang berlaku. Hasil Pemilu dan Pilkada dapat diterima oleh peserta pemilu dan masyarakat. Sehingga menghasilkan pemimpin politik yang memiliki legitimasi untuk menjalankan roda pemerintahan selama 5 (lima) tahun kedepan. Itu artinya separuh dari modal persatuan atau solidaritas masyarakat sudah dapat diwujudkan melalui proses politik yang baik dan sehat. Dalam Hal ini lembaga pemilu seperti KPU, BAWASLU, dan DKPP menjadi leading sektornya. Tinggal selanjutnya, separuh solidaritas lainnya menjadi tanggung jawab Pemimpin Politik terpilih untuk mengisi 5 (lima) tahun masa baktinya kedepan dengan program dan kebijakan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Seorang pemimpin politik harus memaknai kekuasaan yang diperolehnya sebagai barang amanat. Amanat yang ia peroleh dari masyarakatnya. Kesadaran etis ini penting diresapi dan hayati oleh pemimpin politik agar tidak mengalami disorientasi didalam menggunakan kekuasaannya. Pemimpin politik harus ingat ada seribu satu persoalan dan seribu satu harapan di masyarakat. Beragam permasalahan pada masyarakat kota seperti kemacetan, kemiskinan, pendidikan, kriminalitas, dan sebagainya. Apalagi saat ini dunia sedang dilanda masalah kesehatan yakni pandemi covid-19. Maka, peran pemimpin politik sangat dinantikan dan diharapakan kehadirannya. Dalam upaya mengurai berbagai permasalahan di Masyarakat. Seorang pemimpin politik harus mempunyai kapasitas kepemimpinan politik. Kepemimpinan politik yang transformatif sangat dibutuhkan. Pemimpin politik menjadi tumpuan dan menjadi leading sektor dalam upaya mengatur dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Hanya dengan cara ini, kepercayaan publik akan tetap terjaga dan setengah solidaris politik selanjutnya dapat terwujud secara utuh dan menjadikan masyarakat semakin bersatu, kuat, dan makmur. ** Komisioner KPU KOTA BEKASI 2018-2023